Tahun 2013 lalu, seorang pria berusia 35 tahun yang bekerja sebagai PNS (pegawai negeri sipil), tengah berdiri di atas sebuah mobil di antara kerumunan para pengunjuk rasa di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Pemuda itu bernama Mika Ganobal. Ia berkelakar untuk membakar semangat orang-orang. Potret itu menggambarkan perubahan wajah Indonesia setelah 15 tahun Reformasi.
Tentu saja, tindakan semacam itu tidak mungkin dilakukan saat kita masih terjerat rezim militer Orde Baru. Kita tidak terpikir untuk bisa berdemonstrasi di jalan-jalan untuk menentang pemerintah maupun perusahaan. Pemerintah yang otoriter dan diwarnai dengan berbagai kekerasan, membuat mimpi untuk melawan seolah sekedar angan-angan belaka.
Tetapi, aksi tersebut juga menunjukkan sisi lain di mana Indonesia sepertinya belum juga berubah. Hampir setelah satu dekade masyarakat untuk pertama kalinya dapat memilih langsung kepala daerah mereka sendiri, masyarakat Aru justru dikejutkan dengan kenyataan bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Aru telah menjual sebagian besar tanah mereka kepada para investor. Itu dilakukan untuk sebuah proyek perkebunan tebu dalam skala besar.
Kegagalan demokrasi itu terlihat gamblang ketika seorang politisi yang dipilih oleh rakyat, justru telah mengambil keputusan yang bertolak belakang dengan keinginan mereka, bahkan tanpa persetujuan pula. Pemilu langsung, termasuk yang dialami oleh Aru, kemudian mengantarkan seorang kepala daerah punya peluang untuk menentukan kebijakan demi kepentingan perusahaan di atas kepentingan rakyatnya.
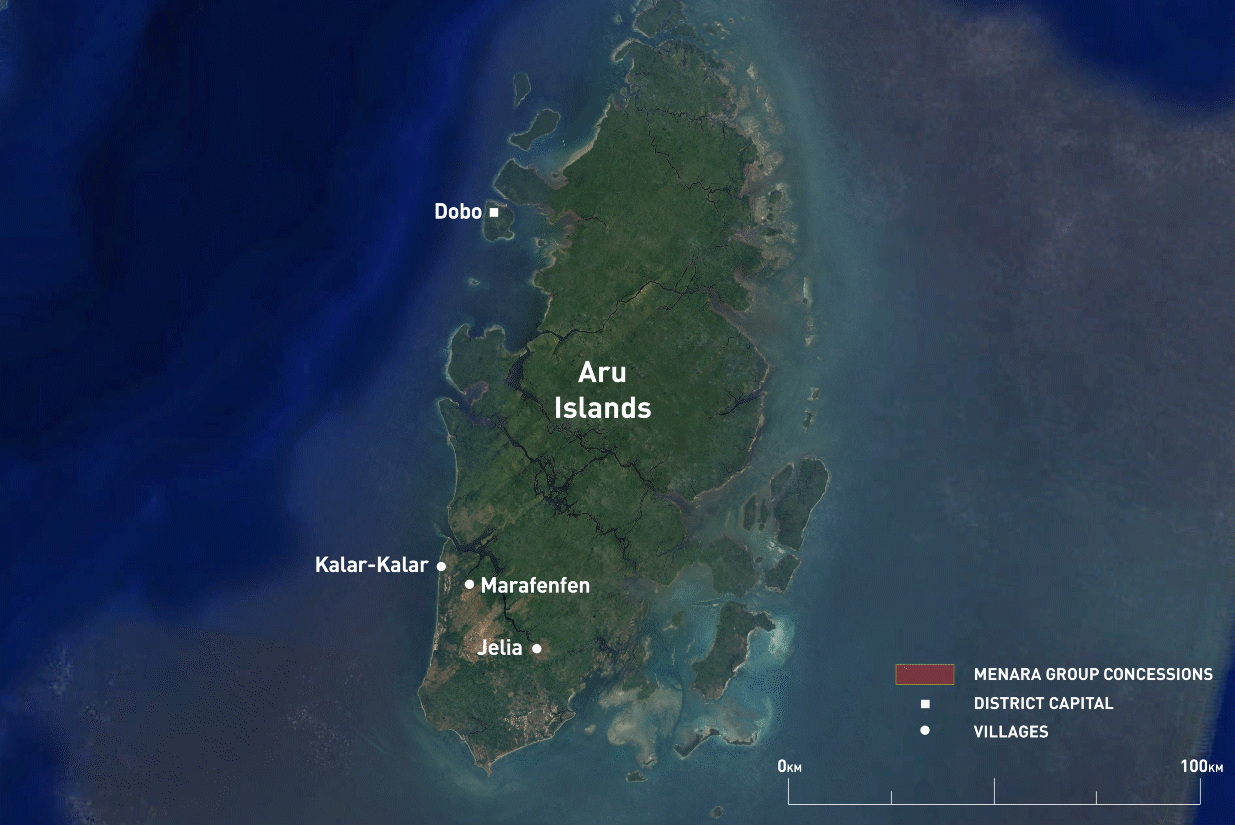
Dalam banyak kasus di mana tanah masyarakat dibebani izin-izin konsesi untuk perusahaan, baik pertambangan maupun perkebunan, muncul suatu isyarat buruk yang sebetulnya dapat mudah dirasakan. Pihak DPRD Kabupaten/Provinsi, polisi, dan kementerian bertindak serempak untuk mendukung pengalihan tanah kepada para investor atau perusahaan tanpa persetujuan di awal dari masyarakat. Dengan ribuan konflik tanah di seluruh Indonesia di mana banyak masyarakat mencoba melawan, pada akhirnya tak sedikit yang kemudian menemui kegagalan dalam menarik perhatian media serta lembaga-lembaga yang berpengaruh di Jakarta.
Tolak ukur dari akuntabilitas demokrasi dapat dilihat dari tindak tanduk kepala daerah yang memegang kuasa terhadap pemberian konsesi. Tetapi, hampir semua badan yang seharusnya punya tugas dalam melakukan kontrol atau pengawasan atas kewenangan kepala daerah itu, ternyata juga gagal menjalankan perannya.
Namun, sesuatu yang berbeda terjadi di Aru. Delapan bulan setelah gerakan tersebut tercetus melalui suatu kampanye yang direncanakan dengan sangat baik, masyarakat Aru akhirnya berhasil mendesak pemerintah untuk membatalkan proyek perkebunan tebu. Ulasan mendalam mengenai hal itu telah ditulis pada artikel panjang berjudul “#SaveAru: Pertempuran Panjang Menuju Kemenangan Gerakan Rakyat” yang dihasilkan melalui kerja sama The Gecko Project dan Mongabay. Masyarakat Aru tidak hanya melakukan aksi unjuk rasa, melainkan juga memancing perhatian jurnalis, mengerahkan potensi media sosial, mencari dukungan para politisi daerah, dan menekan lembaga-lembaga yang berwenang untuk menyelidiki seluk beluk proyek. Keseluruhan kerja-kerja itu bermuara pada pembatalan izin terakhir yang berada di tangan Menteri Kehutanan saat itu.

Pengalaman Aru kemudian memunculkan perenungan: Apakah metode yang dilakukan oleh masyarakat Aru itu dapat direplikasi dalam gerakan sosial pada level akar rumput lainnya dalam upaya mempertahankan hak atas tanah di Indonesia? Pertanyaan tersebut menjadi suatu penanda terhadap titik perubahan penting dalam sejarah politik Indonesia di mana pihak pemerintah justru melakukan serangan balik terhadap hal-hal yang sebetulnya dapat membantu gerakan #SaveAru. Kala negeri ini tengah menuju dekade ketiga dalam babak demokrasi, lantas apakah ada peluang yang kian besar atau justru mengecil bahwa gerakan akar rumput lain akan pula berpotensi untuk bisa menang?
Menyelamatkan Aru
Sejak awal, gelagat proyek perkebunan tebu telah menunjukkan tanda-tanda bahaya. Izin-izin pertama untuk proyek tersebut dikeluarkan oleh Bupati Theddy Tengko dalam waktu hanya satu bulan sebelum ia dijerat karena melakukan tindak pidana korupsi atas penggelapan uang sebesar Rp45 miliar dari dana APBD Kabupaten Kepulauan Aru. Rangkaian izin pun dikeluarkan kurang dari seminggu sebelum ia maju lagi sebagai calon petahana. Selama masa kampanye, Theddy juga telah dituduh melakukan politik uang di mana ia membagi-bagikan sejumlah uang kepada para pemilihnya.
Pada akhirnya, Theddy dihukum atas tindak pidana korupsi anggaran daerah. Namun sesudahnya, tak ada pengawasan terhadap keputusan yang ia ambil kemudian dalam pemberian berbagai konsesi perkebunan terhadap kawasan seluas dua pertiga wilayah Aru. Para aktivis Aru mendapatkan temuan bahwa Theddy telah mengeluarkan izin-izin secara ilegal. Sejumlah izin tersebut ditandatangani tanpa disertai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai persyaratan yang diatur menurut peraturan yang berlaku.
Proyek yang lahir dari politisi yang korup tersebut kemudian telah menerobos aturan hukum di Indonesia sekaligus menerabas batasan-batasan yang seharusnya dapat melindungi masyarakat Aru.
Para aktivis gerakan #SaveAru terus menggali dan berulang kali mengekspos ilegalitas perizinan, studi kelayakan yang cacat secara keilmuan, dan gelombang aksi protes terhadap proyek perkebunan tebu. Mereka pun menggugah pemahaman dan simpati publik menggunakan kanal media sosial yang dibanjiri dengan beragam berita atau informasi, foto, dan infografis yang pula menarik perhatian banyak orang di seluruh Indonesia dan dunia.

Secara cerdik, para aktivis mampu menarik perhatian untuk memperkuat dukungan berbagai pihak, antara lain para akademisi dari Universitas Pattimura Ambon, Gereja Protestan Maluku, seorang legislator DPRD Provinsi bernama Mercy Barends, dua organisasi masyarakat sipil besar berskala nasional, dan seorang musisi terkenal. Tak lama kemudian, para aktivis bersama beragam individu maupun institusi pendukung mereka, meneriakkan hal-hal janggal terkait proyek tersebut.
Hal itu kian menarik perhatian lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki peran dalam pengawasan tata kelola pemerintahan di Jakarta, terutama Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua lembaga tersebut, tidak hanya penting, tapi juga punya jejak rekam yang kerap ditakuti di negeri ini, seperti KPK yang rajin melakukan penangkapan terhadap para pejabat korup kelas kakap.
Pada akhirnya, Zulkifli Hasan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehutanan (kini telah diubah menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), membatalkan proyek tersebut. Tapi di waktu yang bersamaan, kala itu ia pula menandatangani izin-izin yang kemudian menghancurkan kawasan hutan dan wilayah adat di berbagai tempat lain di Indonesia.
Peluang para aktivis untuk bisa menang, sebagian besar tergantung pada perhatian dari lembaga-lembaga yang memiliki pengaruh atau wewenang kuat. Tetapi, untuk bisa menarik perhatian hingga ke sana, dibutuhkan daya dukung ekosistem yang mencakup aksi protes, sorotan media, petisi secara daring, dukungan politisi, dan organisasi-organisasi penekan. Sebab, tak ada yang dapat menghentikan proyek tersebut jika bukan oleh gelombang perlawanan publik yang luas. Dan hal tersebut dapat hidup dan berkembang kian besar di dalam masyarakat yang demokratis.
Metode yang digunakan oleh masyarakat Aru (diuraikan secara lebih detil pada artikel lain yang dibuat oleh The Gecko Project dan Mongabay) bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat manapun yang menghadapi tantangan serupa. Memang tidak semua kampanye sosial dapat melakukan hal atau mendapatkan hasil yang sama seperti yang dilakukan oleh gerakan #SaveAru. Tetapi, prinsip-prinsip dalam mengumpulkan dan mengungkap bukti, menggunakan media sosial yang cerdas, dan mencari dukungan di mana pun, dapat memberikan dampak.
Meski begitu, kisah Aru merupakan suatu isyarat terhadap seberapa jauh kelompok aktivis perlu bekerja keras dalam upaya menggagalkan proyek yang terbukti cacat. Terlepas dari berbagai ketidakjelasan dalam proyek tersebut, mereka pun harus melakukan banyak hal untuk memastikan proyek benar-benar dapat dibatalkan.
Apa yang terjadi di panggung nasional kemudian kala itu, memberitahu kita bahwa perkembangan politik di Indonesia tampaknya menyadari sesuatu. Dan peristiwa-peristiwa yang menyusul kemudian, menegaskan bagaimana perjuangan untuk mengubah sistem tersebut menjadi sangat penting untuk dilakukan.
Menyelamatkan demokrasi
Proyek perkebunan tebu di Aru dibatalkan dalam waktu hanya beberapa bulan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tahun 2014 lalu. Ia adalah presiden pertama yang berasal bukan dari elit partai politik. Jokowi juga bukan seorang militer. Kemenangannya kala itu menjadi simbol dari kekuatan rakyat (people power). Ia dipilih berdasarkan gelombang kepercayaan bahwa ia dianggap mampu memberikan harapan untuk menyuntikkan kembali semangat Reformasi bagi Indonesia.
Jutaan Masyarakat Adat percaya janji politiknya selama kampanye bahwa ia akan mengakui dan melindungi sebanyak 12,7 juta hektar tanah adat, termasuk di Kepulauan Aru yang menjadi sasaran dari proyek-proyek pemerintah dan perusahaan yang terpusat di Jakarta. Dalam Nawa Cita atau Sembilan Agenda Prioritas, Jokowi berjanji bahwa ia hendak “membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi” serta “menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.”

Pernyataan tersebut jelas dan tegas. Jokowi berencana untuk memperbaiki keseimbangan kekuasaan melalui infrastruktur pemerintah dengan membuat para politisi dan oligarki yang mengendalikan tanah-tanah maupun kawasan perkebunan dan pertambangan untuk bertanggung jawab kepada mereka yang tak berdaya. Secara khusus, ia juga pernah menyinggung upaya untuk memperkuat KPK sebagai lembaga yang paling terpercaya di negara ini dan membuat ciut nyali para elit politik.
Namun, janji terhadap tanah reforma agraria maupun penyeimbangan kembali kekuasaan melalui penguatan lembaga-lembaga pemerintah itu, hanyalah tinggal janji. Masyarakat terus kehilangan tanah-tanah mereka dan konflik agraria kian meruncing tanpa ada penyelesaian yang berarti pada kepemimpinan periode pertama Jokowi. Dan menjelang akhir masa jabatannya, ia akhirnya mengeluarkan kebijakan moratorium sawit melalui Instruksi Presiden №8 Tahun 2018. Selama ini, perkebunan sawit dalam skala besar telah disebut-sebut sebagai pendorong utama berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Akan tetapi, Inpres tersebut tampaknya hanya semacam perban yang menutup luka yang terlanjur jadi borok. Moratorium sawit pun berjalan di tempat dan tidak mampu mengatasi akar persoalan perampasan tanah, baik itu yang terjadi di Aru maupun wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Beberapa bulan yang lalu, ketika Jokowi akhirnya resmi menjabat sebagai presiden untuk yang kedua kalinya, keseimbangan kekuasaan pun terasa telah semakin jauh bergerak ke arah yang kian melenceng. DPR bahkan mengeluarkan sejumlah paket kebijakan (Undang-Undang) yang justru melemahkan demokrasi. Para politisi di Senayan tampaknya terburu-buru mengejar agenda legislasi yang menurut kritik kelompok masyarakat sipil justru hendak semakin menyulitkan distribusi hak dan sumber daya untuk masyarakat miskin dan meningkatkan potensi kriminalisasi terhadap para pejuang HAM atau pembela masyarakat.

Di atas semuanya itu, pengesahan revisi UU KPK juga memberikan ancaman yang memperlemah KPK dalam membasmi tindak pidana korupsi yang mengitari lingkaran kelompok elit. Padahal, Maret lalu, KPK baru saja mengajukan usulan terhadap serangkaian pembaharuan yang berbeda di mana hal tersebut akan dapat memberikan peluang lebih besar bagi KPK untuk menjerat pejabat atau politisi yang kedapatan menjual tanah-tanah maupun izin-izin konsesi dengan memaksa pengadilan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari korupsi.
Pada Februari 2020 lalu, pemerintah juga telah mengusulkan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja — atau akrab kita sebut sebagai Omnibus Law — kepada DPR. Berbagai pasal dalam draf tersebut kemudian banyak menuai protes, mulai dari pengabaian aspek ekologi hingga pelemahan sanksi hukum terhadap korporasi. Berbagai kalangan khawatir draf yang kerap disebut sebagai “undang-undang sapu jagat” itu sengaja dihadirkan hanya untuk mengakomodasi kepentingan pebisnis dan justru kelak kian menyulitkan kehidupan rakyat.
Serangan-serangan tersebut tentu saja dapat mengikis sistem dukungan terhadap situasi demokrasi di Indonesia. Bukan tidak mungkin seandainya pun kampanye #SaveAru diadopsi di tempat lain, maka dengan kondisi yang belakangan telah berubah, maka keberhasilan yang sama akan kian sulit atau malah tidak terjadi sama sekali. Tetapi, ada keterhubungan serupa yang kemudian terjadi terkait dengan bagaimana masyarakat sipil merespon apa yang terjadi di Aru tahun 2013 lalu dan baru-baru ini. Jika kala itu masyarakat Aru berbondong-bondong memenuhi jalan-jalan di Dobo, begitu pula dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan ribu mahasiswa di depan gedung-gedung parlemen di berbagai kota di Indonesia secara serempak. Keduanya sama-sama dilakukan sebagai upaya melawan balik serangan yang hendak menurunkan derajat demokrasi.
Aksi protes yang didominasi oleh kalangan mahasiswa itu ditujukan kepada segelintir elit atau penguasa yang hendak mengekang kebebasan terhadap hak sipil dan kapasitas masyarakat sipil untuk berjuang bersama rakyat yang ditindas. Para mahasiswa juga menegaskan kekecewaan terhadap Jokowi sebagai pemimpin yang seharusnya dapat merawat agenda Reformasi. Tindakan-tindakan yang diambil Jokowi menunjukkan potret penting bahwa situasi yang demokratis tidak dapat diinvestasikan hanya pada tataran eksekutif, melainkan pula disandarkan pada institusi-institusi yang justru dapat memiliki wewenang untuk menindak yang berkuasa sekalipun.
Para mahasiswa telah menerjemahkan berbagai tuntutan yang luas dan penting untuk menyeimbangkan kekuatan pemerintah, membendung arus perusakan lingkungan yang selama ini diawasi, dan mencegah kriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan tanah maupun hutan. Kini, perjuangan masyarakat di tingkat akar rumput semacam Aru serta tempat-tempat lainnya, bermuara pada kesadaran di tataran nasional. Aksi unjuk rasa yang dilakukan tersebut menegaskan suatu kepercayaan yang mendalam terhadap prinsip-prinsip mendasar yang sama dan mengalir pada nadi dan darah seluruh masyarakat Indonesia.
Baik itu protes yang terjadi di Aru maupun aksi puluhan ribu mahasiswa yang turun ke jalan-jalan di berbagai kota besar di Indonesia, telah menarik perhatian dunia. Tahun 2014 lalu, perhatian internasional yang tertuju pada Aru turut memberikan tekanan pada lembaga-lembaga pemerintah di Jakarta untuk mencurahkan keseriusan pada nasib Aru ke depan. Kali ini, dengan memasang mata dan telinga secara jeli pada kepemimpinan Jokowi yang baru terpilih lagi, mungkin akan dapat membantu agar sorotan tidak kembali luput. Bahwa korupsi dan pelanggaran HAM bisa jadi batu sandungan yang malah menghambat visi pembangunan ekonomi yang tengah digadang-gadang. Sebuah koalisi yang terdiri dari hampir 100 organisasi dari seluruh dunia, telah mendesak pemerintah untuk menegakan prinsip-prinsip anti-korupsi yang disepakati dalam forum-forum internasional.
Pada akhirnya, kampanye #SaveAru menjadi pembelajaran berharga sebagai pengingat bahwa dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, gerakan sosial dapat menggugat pertanggungjawaban pemerintah, bahkan saat tuas kekuasaan sedang dicengkeram kuat-kuat oleh para penguasa.
Pasca-keruntuhan Soeharto, Indonesia kerap kali dielu-elukan oleh masyarakat global sebagai negara demokrasi yang besar dan sukses karena telah menerapkan pemilu langsung yang bebas dan adil. Namun, tindakan mantan Bupati Theddy Tengko pada satu dekade lalu maupun Jokowi belakangan ini, memberikan potret buram yang menunjukkan keterbatasan pemilu sebagai wujud dari akuntabilitas politik. Mereka adalah bukti bahwa demokrasi tidak selalu bertumpu pada pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan pada rakyat itu sendiri dan institusi-institusi yang seharusnya dapat meminta pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin atau pejabat publik yang telah dipercaya dan dipilih secara langsung.
Berbagai artikel, foto, maupun video yang diproduksi oleh The Gecko Project, tersedia juga pada media sosial kami, antara lain Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Kamu juga bisa terhubung dengan kami melalui milis (mailing list) di sini.


